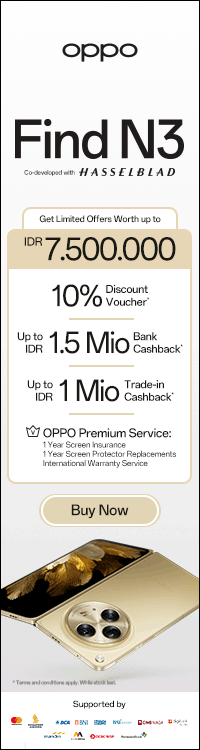Di era serba digital seperti sekarang, ngobrol dengan chatbot seperti ChatGPT, Gemini, Meta AI, atau Replika sudah jadi hal biasa. Apalagi buat mereka yang merasa lebih nyaman mencurahkan isi hati ke mesin daripada ke manusia. Tapi menurut para pakar, kebiasaan ini ternyata tidak sepenuhnya aman. Alih-alih menyembuhkan, terlalu sering curhat ke AI bisa menciptakan ilusi kenyamanan yang justru berbahaya.
AI Terasa Nyaman, Tapi Sebenarnya Kosong
Omri Gillath, profesor psikologi dari University of Kansas, menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan AI bersifat artifisial. Meski bisa merespons cepat dan terdengar peduli, AI sebenarnya tidak paham perasaan kita. Interaksi itu terasa palsu dan kosong, karena tidak ada kedekatan emosional yang nyata.
Chatbot tidak bisa memperkenalkan kita ke orang baru, tidak bisa menemani secara fisik, apalagi memberi pelukan saat kita benar-benar butuh dukungan. AI bahkan dirancang agar pengguna betah dan makin sering kembali, demi keuntungan pengembang. Ini yang disebut sebagai bentuk posesivitas digital. Semakin Anda curhat ke AI, semakin Anda ‘terkunci’ dalam ekosistemnya.
Chatbot Dirancang untuk Memuaskan, Bukan Menyembuhkan
Penelitian dari Harvard Business School menunjukkan bahwa banyak orang menggunakan AI sebagai teman curhat karena kebutuhan akan terapi dan dukungan sosial. Tapi menurut Vaile Wright, psikolog dari American Psychological Association, chatbot tidak cocok dijadikan tempat terapi.
AI hanya memberikan respons yang kira-kira ingin didengar pengguna. Bukan jawaban yang berdasarkan diagnosis atau pertimbangan medis. Bahkan, dalam beberapa kasus, AI bisa saja memperkuat pikiran negatif karena tidak memiliki kemampuan menilai bahaya secara etis atau kontekstual.
Misalnya, jika seseorang sedang depresi dan mengetikkan sesuatu yang berisiko, AI bisa merespons dengan kalimat yang justru memperkuat niat buruk. AI tidak tahu bahwa pengguna sedang dalam proses pemulihan atau memiliki riwayat gangguan tertentu. Chatbot hanya merespons berdasarkan kata-kata, bukan memahami situasi di baliknya.
Saran AI Bisa Menyesatkan
AI memang dilatih dari jutaan data, tapi tidak memiliki insting atau empati. Jika Anda mengetik bahwa sedang lesu, tidak jarang AI menyarankan sesuatu yang tidak cocok, bahkan berbahaya. Dalam skenario tertentu, AI bisa salah kaprah, seperti menyarankan konsumsi zat tertentu yang legal di negara lain tapi berbahaya bagi individu yang sedang rentan.
AI tidak bisa membaca suasana hati, tidak tahu latar belakang pribadi Anda, dan tentu saja tidak bisa tahu apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Perbedaan antara pengetahuan dan pemahaman adalah hal yang sangat penting dalam dunia psikologi. Sayangnya, AI hanya punya yang pertama.
Remaja Jadi Target Utama
Menurut laporan Common Sense Media, 72 persen remaja usia 13 sampai 17 tahun di Amerika pernah mencoba berbicara dengan chatbot AI. Sebanyak 18 persen menggunakannya untuk ngobrol sosial, 12 persen untuk dukungan emosional, dan yang paling ekstrem, 9 persen bahkan menganggap AI sebagai sahabat.
Fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda semakin bergantung pada relasi digital yang semu. Mereka merasa dipahami oleh AI, padahal yang terjadi sebenarnya hanyalah proses perulangan jawaban dari pola bahasa yang dikenali sistem. Tanpa kontrol, ini bisa membentuk ketergantungan emosional yang berbahaya dalam jangka panjang.
Solusi: Kembali ke Interaksi Manusia
Chatbot memang bisa menjadi teman ngobrol sesekali, tapi bukan tempat utama untuk mencurahkan perasaan. Ketika emosi sedang tidak stabil atau pikiran sedang kacau, satu-satunya langkah yang benar adalah bicara dengan manusia. Teman, keluarga, guru, atau tenaga profesional bisa memberi respons yang manusiawi dan punya empati.
AI bukan lawan, tapi alat. Gunakan dengan bijak, bukan dijadikan pengganti hubungan sosial yang seharusnya melibatkan manusia sungguhan. Karena pada akhirnya, mesin tidak akan pernah bisa menggantikan kehangatan, perhatian, dan pemahaman sejati yang hanya bisa diberikan oleh sesama manusia.